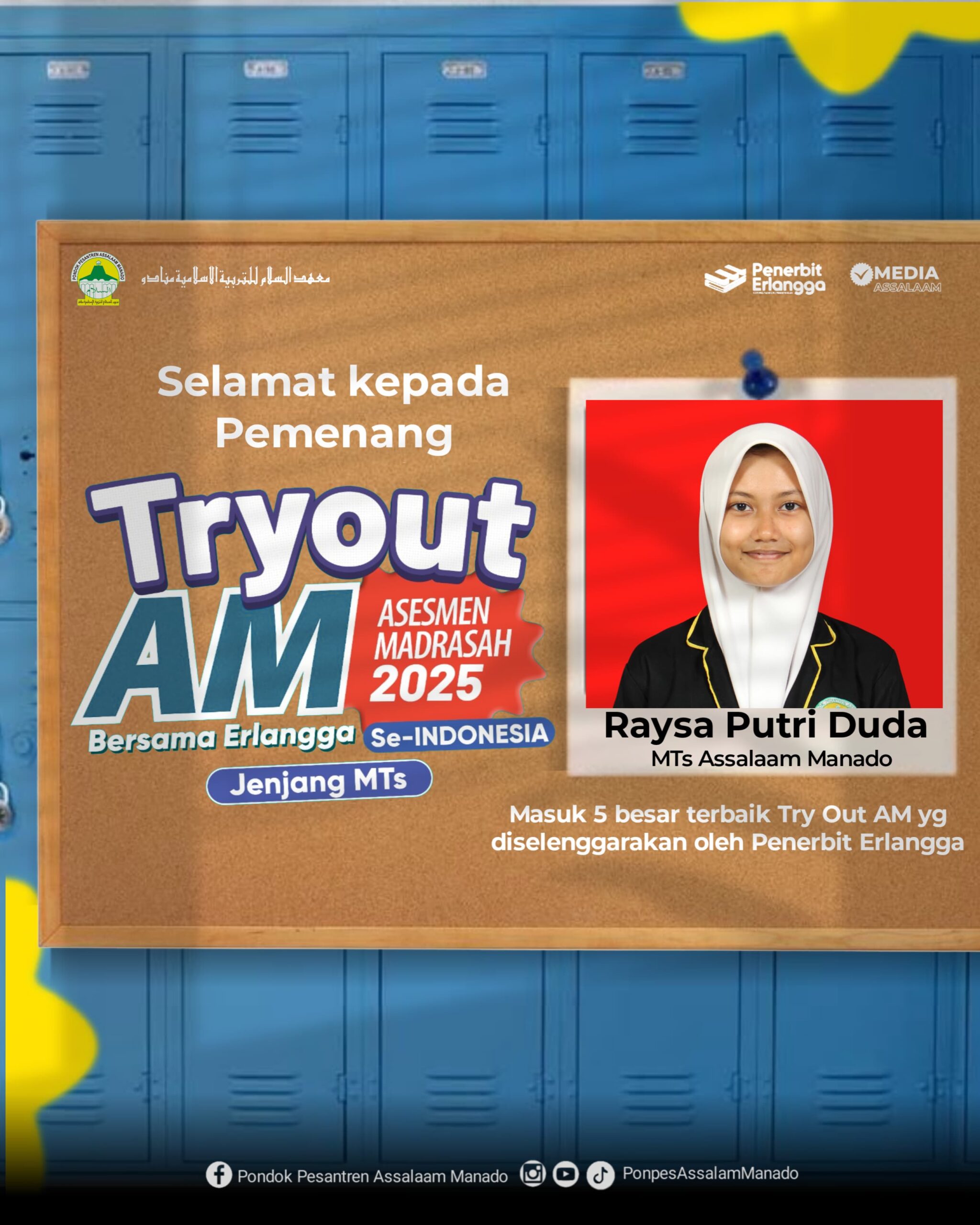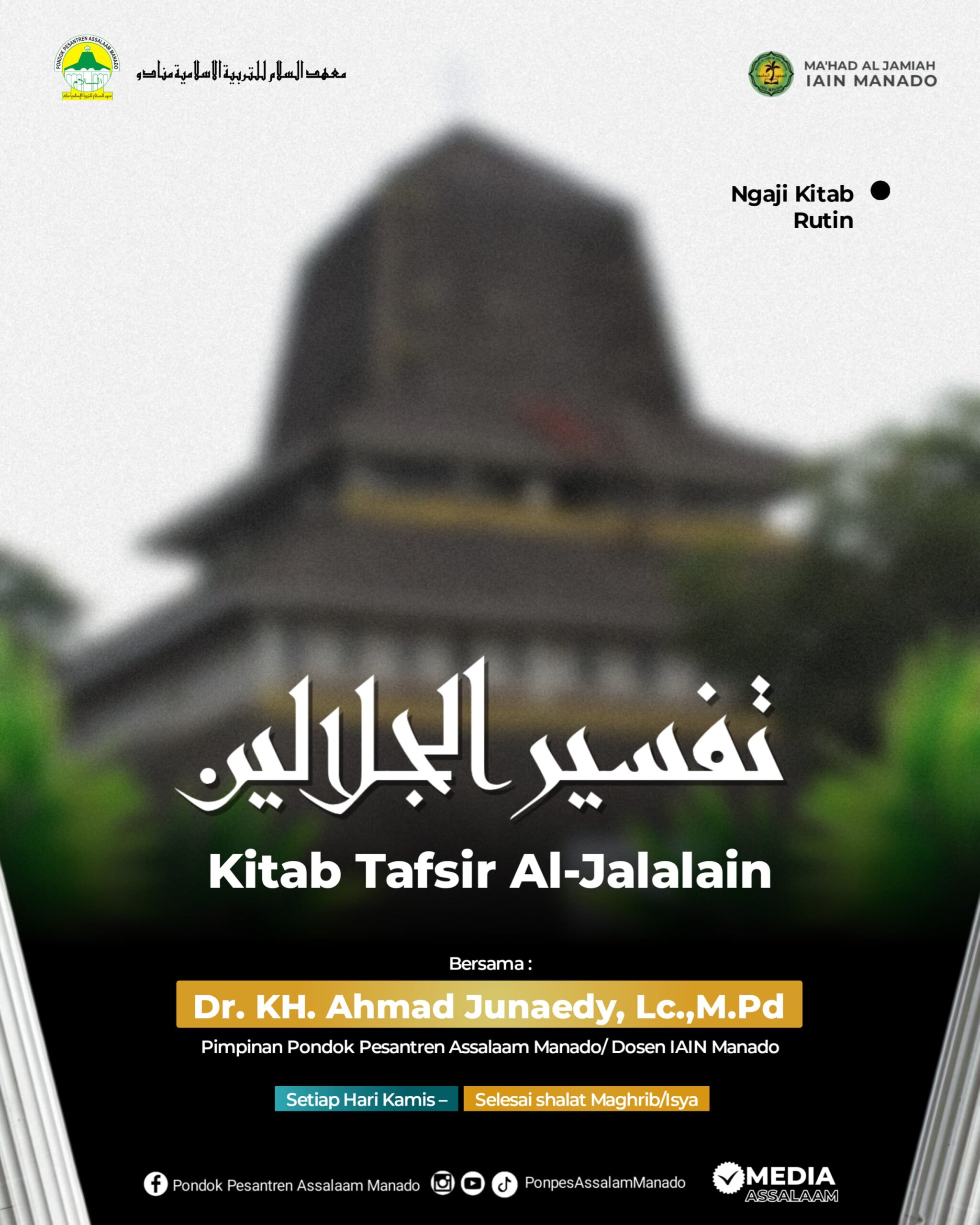Oleh : Masri Hamzah (Staf Pembina Pondok Pesantren Assalaam Manado, Pengurus PERGUNU Sulawesi Utara, Pengurus FUAPP Sulawesi Utara)
Sekolah, sejatinya, adalah ladang ilmu. Di sana, guru menanam benih pemahaman dan memupuk karakter. Namun, belakangan ini, ladang itu terasa gersang. Guru yang dulu digugu dan ditiru, kini lebih mirip pesakitan yang harus waspada setiap kali mendisiplinkan murid. Salah sedikit, bisa berakhir di kantor polisi.
Kasus guru dilaporkan karena tindakan kekerasan terhadap murid bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga cerminan kegagalan kita sebagai masyarakat dalam memahami batasan disiplin, tanggung jawab, dan etika pendidikan. Ada yang melihat guru sebagai satu-satunya pihak yang bersalah, sementara ada yang membela mereka mati-matian. Yang luput dari perdebatan ini adalah satu pertanyaan mendasar: apakah kita masih punya kompas moral yang sama dalam mendidik anak-anak kita?
Krisis ini makin diperparah oleh fenomena yang lebih mengerikan: orang tua yang menjadikan media sosial sebagai palu godam untuk menghancurkan kredibilitas guru atau sekolah. Ada kejadian di mana seorang murid dihukum karena berulang kali melanggar aturan, lalu orang tuanya datang bukan berdiskusi lebih dulu, tetapi langsung merekam secara live di media sosial.
Mereka mengambil sudut paling dramatis, menampilkan wajah anak yang menangis, menuduh guru bertindak sewenang-wenang, tanpa memberi kesempatan bagi pihak sekolah untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dalam hitungan menit, video itu viral. Netizen yang hanya melihat dari satu perspektif langsung memberikan vonis: guru itu kejam, sekolah itu tidak layak dan berbahaya.
Yang lebih menyedihkan, ada orang tua yang sengaja menjadikan viral sebagai strategi untuk menekan sekolah agar tunduk pada keinginannya. Mereka ingin anaknya tetap diterima, tetap mendapatkan fasilitas terbaik, tetapi tidak mau anaknya didisiplinkan. Bukankah ini pola asuh yang sangat kontradiktif?
Fenomena ini bukan hanya menghancurkan reputasi guru, tetapi juga membahayakan iklim pendidikan secara keseluruhan. Bayangkan, bagaimana seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika setiap tindakan mendisiplinkan bisa berubah menjadi drama viral? Bagaimana sekolah bisa mempertahankan standar kedisiplinan jika ancaman media sosial selalu mengintai?
Yang paling sering menjadi bulan-bulanan dalam isu ini adalah pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan disiplin ketat dan nilai-nilai keagamaan, pesantren justru kerap menjadi sasaran amarah orang tua ketika anak mereka mengeluh tentang penegakan aturan di sana.
Padahal, masuk pesantren bukanlah seperti masuk taman bermain. Ini adalah lembaga yang sejak awal dirancang untuk menempa kemandirian, ketahanan mental, dan kedisiplinan santri. Tapi kini, banyak kasus di mana orang tua yang dulu rela “menyekolahkan anaknya ke pesantren agar menjadi anak soleh dan solehah,” tiba-tiba berubah jadi aktivis hak asasi ketika mendengar anaknya kena tegur atau dihukum karena melanggar aturan.
Lebih ironis lagi, sering kali santri yang kabur dari pesantren karena tidak kuat menghadapi aturan ketat justru mendapat pembelaan penuh dari orang tuanya. Pesantren yang selama ratusan tahun telah melahirkan ulama, pemimpin, dan cendekiawan, kini harus berhadapan dengan tuntutan hukum karena dianggap terlalu keras dalam mendidik. Ini pertanda bahwa kita sedang mengalami krisis pola asuh dan persepsi terhadap pendidikan karakter.
Lantas, apa solusinya? Pertama, hukum pendidikan harus disosialisasikan secara luas agar semua pihak—guru/ustaz, orang tua, dan murid—memahami batasan disiplin yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, sekolah dan pesantren harus menjadi ruang dialog, bukan arena konflik. Perlu ada pertemuan berkala antara guru/ustaz, orang tua, dan santri untuk menyepakati kode etik dalam mendisiplinkan. Jika perlu, buat kontrak yang ditandatangani bersama agar semua pihak memahami konsekuensi dari aturan yang telah disepakati.
Namun, mari kita realistis. Ada kondisi di mana tindakan fisik mungkin diperlukan sebagai upaya terakhir setelah upaya yang lainnya gagal, terutama bagi murid atau santri yang berulang kali melanggar aturan. Tetapi, batasannya harus jelas: hanya bagian tertentu yang boleh disentuh, tanpa unsur kemarahan atau dendam. Sekolah dan pesantren harus merancang mekanisme disiplin yang tidak hanya melindungi murid, tetapi juga menjaga marwah guru, ustaz, kiai, kepala sekolah, agar mereka tak selalu berada di ujung tanduk.
Penting juga bagi para guru dan ustaz untuk dibekali pelatihan manajemen emosi dan teknik pengelolaan kelas yang lebih humanis. Disiplin tidak selalu harus dengan hukuman, tetapi bisa dengan membangun kesadaran. Seorang guru atau ustaz yang mampu mengendalikan emosinya dan berkomunikasi dengan baik akan lebih dihormati daripada yang hanya mengandalkan bentakan.
Dan bagi para orang tua, mari kita lebih bijak dalam menyikapi permasalahan di sekolah atau pesantren. Jangan buru-buru merekam dan memviralkan. Sebelum tangan kita gemetar mengetik “tolong viralkan,” coba tanyakan: apakah ini akan menyelesaikan masalah atau justru merusak pendidikan anak-anak kita sendiri?
Jika terus dibiarkan tanpa solusi, pendidikan kita akan berada di persimpangan yang membingungkan. Guru dan ustaz semakin takut mendisiplinkan, murid dan santri semakin sulit diarahkan, dan orang tua semakin mudah menyalahkan. Kita tak bisa lagi membiarkan sekolah dan pesantren berubah menjadi medan perang antara pendidik dan orang tua, apalagi antara pendidik dan hukum. Karena jika itu terjadi, anak-anak kita yang akan menjadi korban sesungguhnya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya “siapa yang salah?” dan mulai mencari jalan tengah. Sebab, di tangan guru dan ustaz yang dihormati serta murid dan santri yang memahami batasannya, pendidikan akan menemukan kembali esensinya: bukan sekadar mengajar, tetapi mendidik.